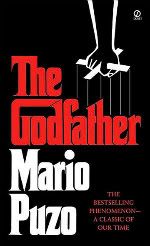Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI merupakan perlindungan yang diberikan terhadap kekayaan intelektual sehingga si pemilik dapat menggunakan dan memanfaatkan kekayaan secara maksimal. Perbincangan tentang HAKI kembali mengemuka ketika Malaysia mulai melakukan klain terhadap beberapa budaya Indonesia. Indonesia sebenarnya telah mempunyai undang undang (UU) HAKI yang diatur dalam tujuh UU yaitu UU Hak Cipta, UU Merk, UU Paten, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Desain Industri, UU Rahasia Dagang dan UU Perlindungan Varietas Tanaman.
Banyak dari masyarakat yang sangat awam dengan tujuh UU tersebut. Beberapa orang mengetahui tentang adanya UU Hak Cipta. Tetapi seringkali mereka mencampuradukkan antara Hak Cipta, Merk dan Paten. Ketiganya memang mempunyai kemiripan meskipun sebenarnya ada perbedaan yang bersifat mendasar. Pernah artis Peggy Melati Sukma menyatakan bahwa ia akan mendaftarkan hak paten atas kata pusiiing yang sering ia ucapkan dan akhirnya menjadi kata populer yang ditiru oleh masyarakat dan artis-artis lain. Pernyataan tersebut jelas tidak tepat sebab paten berhubungan dengan teknologi sedangkan kata pusiiing lebih mengarah kepada hak cipta. Satu hal lagi, pendaftaran sebuah produk bisa dilindungi oleh lebih dari satu UU, misalnya kursi mebel ukir dari Jepara dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta, UU Merek dan UU Desain Industri. Berikut ini penulis berikan gambaran singkat tentang ketujuh UU tersebut:
1. UU Hak Cipta / UU No 15 Tahun 2002
Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Ciptaan tersebut harus merupakan karya asli dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Dalam kasus suatu karya tidak diketahui penciptanya, maka pemegang hak cipta adalah negara, misalnya peninggalan sejarah, benda budaya dan hasil kebudayaan rakyat seperti cerita, hikayat, dongeng, lagu, tarian, kerajinan tangan dll. Jadi pemilik hak cipta atas tari pendet, reog ponorogo, wayang dll adalah negara.
2. UU Merk / UU No 15 Tahun 2001
Merk adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan nama atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Sengketa merk sering terjadi karena sebuah perusahaan yang telah memiliki brand merasa ditiru oleh perusahaan lain. Misalnya sengketa antara merk aqua dan merk aquaria.
3. UU Paten / UU No 14 Tahun 2001
Paten merpakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Contohnya adalah paten terhadap mesin pendingin (refrigerator)
4. UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu / UU No 32 Tahun 2000
Desain terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen. Contohnya adalah rangkaian sirkuit pada mesin-mesin yang bersifat elektronik.
5. UU Desain Industri / UU No 31 Tahun 2000
Desain industri adalah kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi. Misalnya desain sebuah meja.
6. UU Rahasia Dagang / UU No 30 Tahun 2000
Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum dalam bidang teknologi dan/atau bisnis. Contoh rahasia dagang adalah resep masakan atau bumbu KFC
7. UU Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) / UU No 29 Tahun 2000
PVT adalah perlinudungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan melalui pemuliaan tanaman. Misalnya varietas baru Bunga Anggrek.
Sekali lagi, sebuah produk dapt didaftarkan untuk dilindungi oleh lebih dari satu UU. Untuk mengkonsultasikan produknya, maka masyarakat dapat menanyakan pada konsultan HAKi (klinik HAKI)
Sekarang ini istilah Markus (makelar kasus) seolah menjadi pembicaraan hangat, meskipun di kalangan tertentu kata-kata tersebut sudah sangat akrab. Kemunculan markus dalam kasus Cicak Vs Buaya membuat markus seolah diibaratkan fenomena snowball, yang semakin lama semakin kuat dan akhirnya menghantam dan meluluhlantakkan segala apa yang ada disekitarnya. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka jangan-jangan para cenayang pun suatu hari akan terkena “bola salju made in markus” tanpa sempat meramalkannya terlebih dahulu. Kalau sudah begitu tidak tahu lagi apa yang akan terjadi.
Sebelum semua itu akan memuncak, sepertinya kita harus balik lagi ke titik awal dalam kancah berfikir, kenapa markus bisa ada di negeri kita tercinta ini? Mungkin dengan pertanyaan sederhana tersebut kita bisa mendapatkan jawaban yang sederhana pula sehingga mudah untuk dicerna oleh siapapun. Berpijak kepada teori penegakan hukum Soerjono Soekamto, faktor-faktor penegakan hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah law enforcement yaitu:
1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Saat ini yang menjadi sorotan yang sangat-sangat menyedot perhatian setiap orang adalah faktor penegak hukum, terutama kasus Cicak versus Buaya. Ruang lingkup penegak hukum sangat luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, maka yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokat dan lembaga pemasyarakatan atau yang dikenal dengan Criminal Justice System.
Kembali pada permasalahan adanya Markus, tidak lain adalah seperti pada perkataan bang napi, mengutip dari salah satu acara di salah satu televisi swasta. Kata Bang NAPI: “Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, tapi kejahatan bisa terjadi karna ada kesempatan, waspadalah! waspadalah!”
Bahwa timbulnya Markus tidak lain dikarenakan adanya kesempatan. Kesempatan apa yang dapat timbul dari masalah ini, tidak lain adalah karena kesempatan yang ditimbulkan dari para aparat penegak hukum sendiri. Sehingga keberadaan markus makin merajalela melenggang dalam pengadilan. Sebenarnya pengaturan untuk mencegah terjadinya markus sebenarnya sudah ada yaitu dengan adanya kode etik pada tiap aparat penegak hukum atau kita lebih kenal dengan Etika Profesi Hukum.
Seharusnya para aparat penegak hukum harus merenungkan kembali apa itu etika profesi hukum yang akhirnya terejawantah dalam kode etik profesi hukum. Istilah etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian, keterampilan, kejuruan tertentu. Sedangkan kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam profesi hukum.
Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap mayarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama. Dan oleh karena itulah dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut;
1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.
Sinergiditas antara etika profesi dan kode etik adalah seperti kita ambil dari Yap Thiam Hiem, dalam bukunya “Masalah Pelanggaran Kode Etik Profesi Dalam Penegakan Keadilan dan Hukum”, maksud dan tujuan kode etik ialah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik jadinya merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.”
Dari uraian di atas sesungguhnya Markus tersebut seharusnya sudah tidak dapat lagi hadir dalam criminal justice system kita, jika para unsur catur wangsa (hakim, jaksa, polisi, advokat) penegak hukum di Indonesia telah benar-benar comit dengan kode etik masing-masing. Dengan kata lain jangan ada celah-celah kecil yang makin lama makin meluas (efek kapilaritas) yang akhirnya dapat mengaburkan suatu permasalahan yang sedang terjadi.
Persoalan yang menyeruak dan menjangkiti hukum di Indonesia saat ini lebih disebabkan karena terjadinya degradasi moral dalam tubuh aparatur penegak hukum kita. Dalam benak penulis, momentum saat ini dapat menjadi langkah awal pemerintah bersama jajaran institusi penegak hukum, akademisi hukum dan pihak lain terkait penegakan hukum, untuk merekonstruksi kode etik profesi hukum dimana substansinya harus jauh lebih accountable (tanggung jawab). Lebih tegas menutup celah-celah penyelewengan hukum, sangat jelas dan transparan serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Pembenahan etika aparatur penegak hukum seharusnya menjadi salah satu agenda pemerintah dalam mereformasi institusi penegak hukum.
Jadikan kode etik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas profesi hukum yang tidak lain adalah untuk selalu mengacu pada tujuan hukum yang tidak lain adalah mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia.
keterbatasan modal, informasi, manajemen, keahlian, dan teknologi untuk mengubah sumber daya ekonomi potensial menjadi sumber daya ekonomi produktif.
Indonesia termasuk dalam kelompok negara berkembang tersebut dan secara faktual sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing telah membuka akses kepada investor asing untuk ikut “menikmati” potensi alam Indonesia yang kaya. Berbagai upaya dilakukan untuk menarik investor asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia dengan harapan segera mampu mewujudkan tujuan nasional yang tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.
Hubungan antara pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan perusahaan asing dibuat melalui serangkaian negosiasi untuk kemudian dituangkan dalam kontrak. Berbagai kontrak telah disepakati, antara lain melalui Kontrak Production Sharing, Kontrak Karya, dan Kontrak Joint Venture. Dalam konteks Indonesia eksistensi sebuah kontrak tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, yakni adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya obyek tertentu, dan adanya kausa yang halal. Kontrak yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut akan menimbulkan konsekuensi yuridis mengikat seperti undang-undang bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya dengan penuh itikad baik.
Prinsip umum yang berlaku dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak (freedom of contract principle). Melalui prinsip ini para pihak bebas menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan sekaligus bebas untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Penyelesaian sengketa (dispute resolution) merupakan unsur aksidentalia dalam sebuah kontrak yang sifatnya terbuka (open system). Walaupun demikian terkadang para pihak tidak memasukkan pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum (choice of forum) dalam kontrak yang mereka buat entah karena kelalaian atau memang kesengajaan.
Sengketa dagang internasional adalah sengketa dagang yang timbul dari hubungan dagang internasional berdasarkan kontrak maupun tidak. Dalam formulasi pertama, sengketa dagang internasional dapat menyangkut substansi kontrak maupun mengenai hukum yang berlaku terhadap kontrak itu. Sengketa apapun bentuknya pada hakikatnya merupakan masalah yang diusahakan untuk dihindari oleh para pihak, karena adanya akan menghambat proses bisnis yang umumnya berpengaruh terhadap efisiensi waktu, biaya, dan bonafiditas perusahaan.
Oleh karena kontrak dalam konteks ini mengandung elemen-elemen asing, maka dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai persoalan antara lain mengenai hukum manakah yang berlaku (applicable law) atas perjanjian atau kontrak tersebut dan forum (pengadilan) manakah yang berwenang mengadili jika terjadi sengketa hukum antara para pihak. Untuk mencari hukum yang berlaku dalam suatu kontrak yang mengandung unsur Hukum Perdata Internasional dapat dipergunakan bantuan titik-titik pertalian atau titik-titik taut sekunder, diantaranya adalah pilihan hukum (choice of law), tempat ditandatanganinya kontrak (lex loci contractus), atau tempat dilaksanakannya kontrak (lex loci solutionis).
Putusan sebuah lembaga arbitrase berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat final and binding, serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Pada kasus ini putusan yang dihasilkan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 termasuk dalam Putusan Arbitrase Internasional yaitu putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
Saat ini perbincangan mengenai reformasi berbagai aspek kemasyarakatan dan kenegaraan telah menjadi milik kalangan luas masyarakat dan cukup mendominasi tema keseharian kita. Pada pokoknya sebagian besar pengamatan memberi prioritas utama pada perlunya reformasi di tiga aspek, yakni hukum, ekonomi dan politik. Ketiga aspek tersebut boleh jadi mempunyai nilai signifikansi dan bobot yang sama bagi keberhasilan reformasi secara keseluruhan. Namun sayangnya, perhatian atas aspek hukum masih belum sebesar perhatian atas aspek ekonomi dan politik.
Yang mencuat mengenai aspek hukum hanyalah persoalan pencabutan paket lima undang-undang politik dan undang-undang subversi, yang notabene pemberlakuan serta kelangsungannya hanya merupakan hasil dari proses yang menyangkut teknik dan politik perundang-undangan. Tulisan ini sebagai sumbang saran mencoba mendiskusikan apa yang dinamakan dalam tulisan ini sebagai pergeseran paradigma, terutama menyangkut teknik dan politik perundang-undangan dalam pembentukan hukum. Pergeseran paradigma ini menurut pandangan penulis penting diupayakan untuk memberi iklim kondusif bagi pelaksanaan reformasi. Inti pergeseran paradigma tersebut mencakup tiga hal, yakni dari jargon konstitusional menuju pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, dari formalisme menuju substansialisme, dan dari absolutisme menuju dinamisme.
Pertama, pergeseran dari jargon ‘konstitusional’ menuju pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini eksekutif dan legislatif tidak lagi menyembunyikan kepentingannya dalam jargon ‘secara konstitusional’ dalam menanggapi keinginan perubahan. Karena pada intinya atau bila diartikan lebih lanjut, jargon ‘secara konstitusional’ tersebut berkecenderungan untuk tetap mengedepankan peraturan perundangan atau peraturan tata tertib yang memangkas kedaulatan rakyat. Sebagai contoh di antaranya adalah penggunaan hak-hak DPR, seperti hak inisiatif, amandemen dan budgeter dalam pemberdayaan potensi perancangan maupun korektif DPR terhadap kinerja pemerintahan. Hak-hak tersebut tidak dapat dipraktekkan secara leluasa, karena belenggu peraturan tata tertib DPR sendiri. Oleh karenanya tidak menjadi aneh apabila pihak legislatif pada kenyataannya lamban dalam menyikapi keinginan perubahan. Hal ini dapat dilihat secara konkrit dalam tanggapan berbagai pihak mengenai press-release Pimpinan DPR/MPR agar Presiden mengundurkan diri. Press-release yang dibacakan tanggal 18 Mei 1998 tersebut, walaupun sifatnya baru merupakan himbauan, bukan Ketetapan atau Keputusan, dianggap menyalahi Undang-undang dan/atau Tata Tertib DPR/MPR.
Semenjak mencuatnya gagasan reformasi, jargon reformasi yang konstitusional kerap dipakai kalangan eksekutif dan legislatif dalam memberikan tanggapan terhadap keinginan reformasi. Namun jargon tersebut terkesan dipergunakan untuk melambat-lambatkan keinginan reformasi, bahkan menyembunyikan kecenderungan mempertahankan status quo. Oleh karenanya jargon ‘secara konstitusional’ dipandang oleh banyak pihak sebagai tanda bagi kelumpuhan paradigma (paradigm paralisys) dinamika kehidupan bangsa melalui jalur formal. Padahal akan berbahaya sekali bilamana kesadaran kelumpuhan tersebut berujung pada pikiran bahwa tidak ada jalan lain bagi perubahan, kecuali melalui revolusi.
Jalan terbaik yang mendesak diupayakan sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai sebuah bangsa berani kembali kepada kemurnian pelaksanaan pasal-pasal undang-undang dasar kita, dan bukannya menggunakan peraturan perundangan organik atau peraturan tata tertib yang pada kenyataannya membuat kedaulatan rakyat menjadi sulit dicapai. Sejarah ketatanegaraan kita pernah melakukan hal yang patut diteladani dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Yakni diadakannya peninjauan kembali produk-produk legislatif Negara yang berupa Ketetapan MPRS dan di luar produk MPRS, yakni yang berbentuk Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, Undang-undang, maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Hal tersebut diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966. Pelaksanaan dua Ketetapan tersebut berhasil melakukan pencabutan beberapa produk legislatif negara, yang isi serta tujuannya dipandang bertentangan dengan suara hati nurani rakyat.
Sebagai tindakan awal yang sejalan dengan paradigma ini, adalah relevan untuk memenuhi tuntutan pencabutan paket lima undang-undang politik. Namun untuk mencapai tahap reformasi yang mencukupi, segala peraturan perundangan dan tata tertib yang menghambat keberdayaan kewenangan legislasi DPR harus secara langsung dicabut dan diganti.
Kedua, pergeseran dari formalisme menuju substansialisme. Dalam hal ini proses pembetukan suatu hukum haruslah pertama-tama didasarkan pada materi atau substansi peraturan perundangan yang bersangkutan, dan bukan pada bentuk peraturan perundangannya. Maksudnya adalah bahwa perlunya kedaulatan rakyat dilibatkan, yang dalam konteks negara kita melalui persetujuan DPR, bukan dilihat bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan akan dituangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundangan di bawah undang-undang, misalnya Peraturan Pemerintah atau Keppres. Namun apakah substansi peraturan perundangan tersebut merupakan materi yang boleh dibentuk oleh eksekutif saja ataukah harus dengan persetujuan legislatif. Sebagai contoh misalnya bahwa selayaknya setiap pembebanan kewajiban, terutama menyangkut ekonomi dan finansial kepada warga negara haruslah mendapat persetujuan DPR. Jadi peraturan perundangannya harus berbentuk undang-undang. Sehingga tidak dapat dituangkan dalam bentuk yang untuk pemberlakuannya tidak memerlukan persetujuan DPR, misalnya Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden.
Saat ini bisa dilihat bahwa peraturan perundangan berbentuk Keppres diberlakukan untuk hal-hal yang membebani secara ekonomis kepada rakyat. Contoh terbaru dari hal ini adalah Keppres Nomor 69 dan 70 tahun 1998 tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan kenaikan Tarif Dasar Listrik. Suatu peraturan perundangan –yang seperti kita ketahui sendiri, dampaknya sangat luas dan strategis terhadap berbagai bidang lain, hanya diatur oleh Keppres yang pemberlakuannya tidak diperlukan persetujuan DPR. Padahal kalau kita pelajari peruntukannya, menurut Surat Presiden yang ditujukan kepada Ketua DPR No. 2262/HK/1959 disebutkan bahwa bentuk peraturan perundangan Keppres dimaksudkan untuk melakukan atau meresmikan pengangkatan-pengangkatan. Jadi Keppres diundangkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat intern kepresidenan dan administrasi kepemerintahan.
Ketiga, pergeseran dari absolutisme menuju dinamisme. Yakni sudah saatnya masuk dalam pemikiran kita membuang jauh gagasan yang hendak mengabsolutkan peraturan perundangan, dimana satu proses dan produk ketatanegaraan masa tertentu bisa membelenggu proses dan produk ketatanegaraan dan kemasyarakatan masa-masa yang akan datang. Setiap dinamika dan perkembangan yang terjadi atau diinginkan bagian terbesar masyarakat harus mendapat tempat dalam proses pembentukan hukum. Sehingga tidak perlu terjadi misalnya suatu konsensus dari satu kelompok masyarakat pada masa tertentu mengabsolutkan keberlakuan dan penafsiran peraturan perundangan. Dalam hal ini, budaya menempatkan amandemen dan addendum yang memang dibutuhkan terhadap suatu peraturan perundangan, tidak dipersulit dengan lingkaran setan aturan mengenai referendum yang berlaku saat ini. Sejalan dengan ini adalah pengamatan DR Adnan Buyung Nasution yang menyimpulkan, bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang bahkan undang-undang dasarnya sekalipun tidak bisa dirubah atau ditambah.
Secara umum upaya terbaik bagi terselenggaranya pergeseran paradigma absolutisme menuju dinamisme adalah dikembalikannya gairah intelektualisme dalam kajian konstitusi di tengah masyarakat kita. Seluruh potensi pemikiran dan kritik dari kalangan yang seluas-luasnya mengenai tema ini perlu diperlakukan sebagai sesuatu yang sah dan dihargai sebagai sebuah partisipasi dalam menegakkan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Tingkat kesadaran ini memang memerlukan satu metode yang perlu dipahami bersama secara lebih mendalam. Yakni bahwa segala proses dan hasil dari kajian konstitusi bukan merupakan suatu doktrin yang ketat, sehingga menjadi tafsir baku yang alergi terhadap kritik dan perbedaan. Segala kajian, baik itu yang bersifat resmi kelembagaan negara, semisal butir-butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), maupun bersifat umum dari kalangan intelektual dan masyarakat, harus diperlakukan selayaknya sebuah ilmu atau diskursus yang setiap saat siap untuk dipelajari dan dikritisi.
Mengenai intelektualisme ini, kita dapat mengambil hikmah dari kegairahan sebagaimana terjadi pada tahap awal kemerdekaan Republik Indonesia sampai dekade pertama dari masa pemerintahan Presiden Soekarno. Seluruh komponen kritis bangsa pada waktu itu ikut berpartisipasi menyumbangkan pemikirannya terhadap konstitusi dan penafsirannya, baik berupa buku, pidato maupun bentuk lain. Bahkan terhadap perancangan undang-undang dasar sendiri terjadi perdebatan penting antara dua kubu yang berlainan konsep dan wawasannya. Yakni yang dalam istilah sekarang sering disebut sebagai kubu integralistik, yang diwakili pemikiran Soepomo dan Soekarno, berhadapan dengan kubu liberal, yang diwakili pemikiran Hatta dan Syahrir.
Selain itu di tingkat undang-undang dasar kita juga bisa belajar dari apa yang pernah dilakukan Konstituante dalam melaksanakan mandatnya untuk menyusun konstitusi baru. Walaupun gagal, namun gairah intelektualisme dan keberanian berfikir dalam tubuh legislatif tetap patut dijadikan contoh bagi DPR sekarang ini. Sedangkan di tingkat undang-undang dan peraturan perundangan di bawahnya, intelektualisme dapat ditumbuhkembangkan salah satunya dengan memberikan hak uji materiil (judicial review), terutama pada komponen yudikatif, yakni Mahkamah Agung. Dengan demikian, secara kelembagaan Mahkamah Agung dapat berfungsi tidak saja sebagai agent of justice, namun juga sebagai the agent of democracy. Dan secara umum, masukan atau koreksi yuridis yang berasal dari masyarakat akan mendapat saluran yang lebih luas, berwibawa, serta sistemik. Sehingga pada gilirannya nanti dapat membantu membiasakan cara-cara demokratis dan berkedaulatan rakyat ke tengah-tengah masyarakat Indonesia.


 Skenarionya didasarkan pada karya novelis Robert Harris yang dibintangi oleh sejumlah aktris dan aktor papan atas Hollywood seperti Ewan McGregor, Pierce Brosnan, serta Kim Cattrall. Dalam 'The Ghost Writer'.
Skenarionya didasarkan pada karya novelis Robert Harris yang dibintangi oleh sejumlah aktris dan aktor papan atas Hollywood seperti Ewan McGregor, Pierce Brosnan, serta Kim Cattrall. Dalam 'The Ghost Writer'.
 Skenarionya didasarkan pada karya novelis Robert Harris yang dibintangi oleh sejumlah aktris dan aktor papan atas Hollywood seperti Ewan McGregor, Pierce Brosnan, serta Kim Cattrall. Dalam 'The Ghost Writer'.
Skenarionya didasarkan pada karya novelis Robert Harris yang dibintangi oleh sejumlah aktris dan aktor papan atas Hollywood seperti Ewan McGregor, Pierce Brosnan, serta Kim Cattrall. Dalam 'The Ghost Writer'.
Juwono Sudarsono Djaka R Sulistyo Ronny Haryanto Angelina Sondakh Icha Rahmanti Dian Sastro W Ninit Yunita The Genggeus
copyright © 2011 | bambangharyanto.co.nr - all rights reserved | design by bambang haryanto - powerd by blogger.com